Menembus ke Relung Mbeliling

Sapaan hangat dan lucu itu sedikit mengusir pegal setelah hampir empat jam kami menempuh perjalanan 63 kilometer, dari Kota Labuhan Bajo menuju Nunang, Flores, pada 14 April lalu. Bersama tim media dari Jakarta, dengan Isuzu Panther Diesel, kami melalap medan jalan licin dan berbatu, menerjang lebih dari lima anak sungai, plus menyusuri sepotong ruas jalan berbalut tanah merah.
Jantung berdesir-desir kencang ketika ban belakang sedikit gundul. Mobil pun harus bolak-balik bekerja keras agar tidak menjerumuskan kami ke dasar tebing di kanan atau kiri jalan.
Nunang, tujuan perjalanan kami, merupakan dusun di Desa Wae Sano, di relung Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kawasan Mbeliling diumpamakan sebagai oasis Flores. Hutan dataran rendah, yang tergolong langka, masih relatif rapat menghimpun sumber air untuk dinikmati penduduk di bagian lain di Bumi Flores. Labuhan Bajo, misalnya. Kota yang menjadi pintu masuk turis "tumpahan" dari Bali menuju Pulau Komodo itu menggantungkan pasokan air bersihnya dari Mbeliling.
"Tidak ada hutan yang tersisa yang seluas Mbeliling di bagian lain Flores," kata Tengku Budi Aulia, ketua tim Burung Indonesia, perhimpunan pelestarian burung liar Indonesia, di Mbeliling.
Di kawasan ini juga masih ditemukan tiga dari empat spesies burung endemi Flores, yakni hehicap Flores, gagak Flores, dan serindit Flores. Bahkan beco (Papagomys armandvellei), si tikus raksasa sebesar musang, masih berkeliaran menjelang tengah malam di pohon-pohon enau.
"Tikus-tikus itu kami santap kalau pas bertemu saja," Henrik Sumur, warga Nunang, mengungkapkan. Kalaupun ingin berburu beco, tutur Henrik, mudah sekali. Tikus-tikus itu tinggal disudutkan lalu dijatuhkan dari atas pohon. Begitu di atas tanah, tikus yang seperti keberatan badan itu pasrah saja di antara salak anjing-anjing yang memang sudah menanti.
Mbeliling juga anugerah. Hutan seluas 30.142 hektare di kawasan ini masih relatif terjaga. Seperti diakui Budi, keterlibatan Burung Indonesia di kawasan ini, dengan membentuk kelompok-kelompok sadar ekowisata, bertujuan mencegah hutan rusak. "Belum sampai memperbaiki," katanya.
Seperti diakui Yoseph Subur, Kepala Desa Wae Sano, masyarakat Nunang mencoba hidup selaras dengan hutan di beranda belakangnya dan danau sebagai kolam peneduh di teras depannya. Mereka bertani padi ladang, ubi kayu, kemiri, cokelat, pinang, sirih, alpukat, dan lainnya sambil mengurangi kebiasaan berburu. Hutan tak lagi mereka jamah selain sebagai apotek hidup dan danau dibiarkan mengumbar aroma belerangnya dengan bebas.
Setelah diterima bermalam di rumah Yoseph Subur, dengan simbol-simbol penyambutan, seperti ayam jantan putih, sebotol bir, sebungkus rokok, dan secarik uang kertas Rp 50 ribu, petualangan kecil kami di Nunang dimulai. Malam itu rumah panggung dari kayu dengan tiga lampu TL yang cuma bisa nyala sampai pukul 22.00 itu memeluk kami dengan kehangatannya.
***
Legenda setempat mengisahkan danau ini terbentuk karena hukuman yang diterima orang buta dan orang lumpuh. Dikisahkan, orang buta membutuhkan api yang dimiliki si lumpuh. Si buta itu lalu mengutus anjingnya membawakan api itu kepadanya. Anjing yang menyumbangkan ekornya untuk membawa api itu ternyata menjadi panik karena terbakar di tengah jalan. Tuannya dan si lumpuh tertawa terpingkal-pingkal.
Dewa marah atas kelakuan kedua manusia itu, lalu memberi dua pilihan: bubur atau nasi. Nah, di sinilah kami yang mendengar langsung kisah ini dari tetua-tetua adat Wae Sano tidak mengerti kenapa bubur yang dipilih menjelma menjadi danau. "Apa hubungannya, ya?" tanya seorang kawan. Bisa jadi maknanya sangat besar, tapi saya cuma bisa mengangkat bahu.
Lupakan saja. Yang jelas, danau ini memiliki garis keliling 7.800 meter, dengan diameter 1.800 meter. Untuk menikmati panorama danau ini, pengunjung bisa meminjam kuda tanpa pelana milik pastoran setempat.
Yang istimewa dari danau ini adalah tiga sumber air panas yang menghiasi satu sudutnya, dekat jalan di pintu masuk Nunang. Tiap-tiap sumber mewakili panas 30 derajat, 70 derajat, dan 100 derajat Celsius. Yang pertama bisa untuk merendam kaki, yang kedua untuk membasuh muka dan tubuh, sedangkan yang ketiga sering digunakan eksperimen menggodok telur dan ubi kayu oleh 30 wisatawan maupun naturalis yang telah datang sepanjang 2008--termasuk kami.
"Keindahan luar biasa Sano Nggoang sudah menanti," begitu kata Yoseph ketika kami datang terlambat pada Selasa itu.
***
Mulai pagi-pagi sekali, pada hari kedua, kami memiliki kesempatan membuktikan keasrian Nunang dan keindahan Sano Nggoang. Hujan yang turun lagi selepas tengah malam masih sangat jelas jejaknya di tanah ketika kami satu per satu menuruni anak tangga rumah panggung Yoseph.
Sedikit melenturkan badan, membereskan ransel, petualangan kecil hari itu kami mulai dengan mendaki bukit di belakang dusun. Puncak Golodewa, yang artinya Gunung Dewa, itulah yang kami tuju. Dari sedikit tanah datar di ketinggian kira-kira 800 sampai 1.000 meter itu, kami disuguhi pemandangan danau biru tertusuk ilalang yang fantastis. Kadang burung kirik-kirik yang sedang mandi cahaya hangat matahari pagi terbang melintas.
Hari itu kami memang tidak beruntung mendapati tiga primadona kehicap, serindit, dan gagak Flores. Satu ekor gagak kami temui, tapi itu sudah di perjalanan pulang menuju Labuhan Bajo keesokan harinya. Ketiga nama burung endemi (cuma ada di sana) itu juga cuma kami dengar secara lengkap dan berulang-ulang dalam lagu yang dibawakan anak-anak desa menyambut para tamu desa, para petinggi dari organisasi Burung Indonesia yang tentu ingin memastikan dana yang mereka himpun tidak tersalur sia-sia.
Adapun pendakian ke Golodewa boleh dibilang cuma makan waktu sejam. Jarak memang tidak terlalu jauh, tapi pendakiannya yang tidak jarang membentuk sudut 45 derajat cukup membuat ransel di punggung terasa berat. Jalan setapak pun seperti baru dirintis sehari sebelumnya, belum terlalu jelas.
"Sebenarnya ada satu puncak savana lagi, Pocodedeng. Golodewa ini baru setengah jalan," kata Henrik, yang memandu kami. "Tapi kita cukup sampai di sini saja." Kecewa, boleh jadi, tapi kami menurut. Sinyal telepon seluler yang tiba-tiba menghubungkan kami kembali dengan dunia di luar Nunang membuat kami cepat melupakan kekecewaan itu.
Selain melihat pohon-pohon bambu superbesar dan kopi hutan, kami berkenalan dengan berbagai tanaman berkhasiat obat di sepanjang perjalanan hingga Golodewa. Ada renggau yang biasa digunakan untuk mengobati flu, tambar untuk malaria, saumene ketika ada yang terserang cacingan, dan mencok yang dipakai wanita setempat membersihkan diri setelah melahirkan.
Masih ada beberapa yang lain yang berguna untuk mengobati keputihan sampai sekadar sakit pinggang. Bahkan ada yang dipercaya bisa menginformasikan keberhasilan janin mirip peran teknologi USG. Nama lokal tumbuhan yang terakhir ini adalah teno. Ketika seorang wanita berhasil mencabut tumbuhan ini beserta akar-akarnya, janin yang sedang dikandungnya diprediksi akan selamat melewati proses persalinan.
Puas menikmati keanggunan dan ketenangan Sano Nggoang dari Golodewa, kami pun beranjak turun kembali ke dusun. Sarapan buatan mama desa (istri kepala desa) dan janji mencicipi bola-bola singkong, menu olahan unggulan kelompok sadar ekowisata Maria Sumur dan kawan-kawannya, membuat langkah kami menuruni jalan setapak terasa lebih ringan.
Keluar dari hutan, kami bertemu dengan jalan seperti bekas aliran sungai yang mengering. Jalan sebentar dari sana, kami sudah bertemu dengan jalan utama desa dengan tepiannya yang dihiasi pagar bambu segar demi menyambut tamu-tamunya dua hari itu. "Selamat, Cole," sapa seorang bocah tiba-tiba di daun jendela di satu rumah panggung. Lah?
Post by :www.tempointeraktif.com

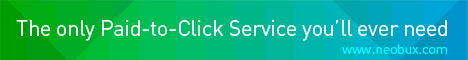
maju terus manggarai barat
BalasHapus